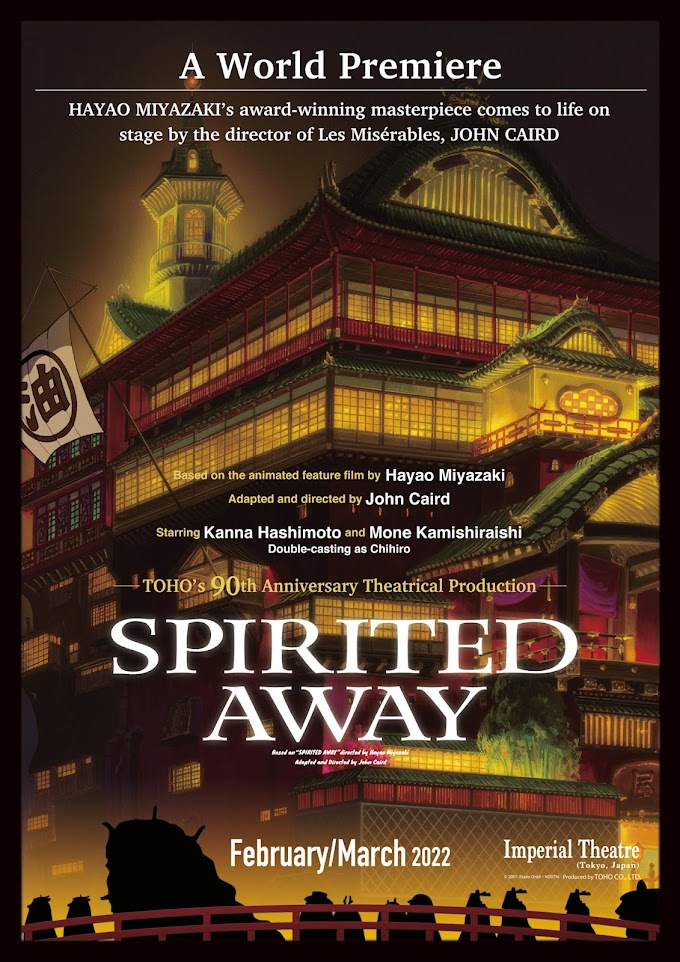Ilustrasi sepasang kekasih.
(Sumber gambar: freepik.com)
Rizky menunduk, jari-jarinya menggenggam erat sebuah foto lama yang sudutnya sudah mulai menguning. Di dalam bingkai kecil itu, ada dua wajah muda yang tersenyum lebar, berdiri di bawah pohon rindang dengan tangan saling bergandengan. Matanya berkaca-kaca, dan sebuah gumaman pelan keluar dari bibirnya, "Kita pernah punya impian." Di belakangnya, suara langkah kaki mendekat, lembut tetapi pasti. Sebuah tangan hangat menyentuh bahunya, dan sebuah suara yang dikenalnya dengan baik bertanya, "Ternyata, kamu sudah sampai di sini duluan?" Ia menoleh, mendapati Vivi berdiri di sana, matanya penuh kelembutan bercampur rasa penasaran.
Mereka duduk bersama di bangku kayu tua yang menghadap laut, angin malam membawa aroma garam yang menyelinap di antara mereka. "Aku tadi meneleponmu untuk datang ke sini, sebenarnya untuk bernostalgia," ujar Rizky, menyerahkan foto itu ke tangan Vivi. Perempuan itu menatap gambar tersebut lama, jari-jarinya mengusap permukaannya seolah mencoba menangkap kembali waktu yang telah hilang. "Waktu itu, kita masih percaya cinta saja cukup," katanya, nada suaranya sedikit bergetar. Rizky tersenyum tipis, pandangannya menerawang ke arah ombak yang bergulung pelan. "Ingat dulu? Kita sering ketemu di tepi pantai ini, jauh dari mata ayahmu yang selalu curiga."
Vivi terkekeh, suaranya ringan tetapi ada jejak kepahitan di dalamnya. "Ia memang tidak pernah menyukaimu. Tapi aku selalu punya cara untuk menyelinap keluar, kan?" Ia menatap Rizky, dan dalam sorot matanya, ada kilasan kenangan tentang malam-malam mereka berdua berlari di bawah lampu jalan, berbisik tentang impian yang terasa begitu nyata.
Namun, keheningan sejenak menggantung di antara mereka, membawa bayang-bayang realitas yang tak bisa dihindari. "Kita punya mimpi besar waktu itu," ucap Rizky, suaranya rendah. "Keluarga, rumah, kehidupan yang sempurna. Tapi sekarang..." Ia tak melanjutkan, tapi Vivi tahu apa yang ada di pikirannya. "Sekarang kita terjebak," sambungnya.
"Aku di kantor itu, menghadapi bos yang tak pernah puas, pulang dengan kepala penuh keluhan, dan tagihan yang menumpuk di meja."
"Aku juga," balas Rizky, tangannya mengepal di sisi bangku. "Kerja di pabrik, gaji yang habis sebelum akhir bulan, dan teman-teman lama yang dulu dekat, sekarang hilang entah ke mana. Rasanya seperti kita lupa siapa kita dulu." Mereka saling bertatapan, dan dalam pandangan itu, ada kerinduan yang membakar—bukan hanya pada masa lalu, tapi pada kebebasan yang pernah mereka yakini bisa mereka raih.
Vivi menggenggam tangan Rizky, jari-jarinya dingin tetapi penuh tekad. "Mungkin kita butuh perubahan," katanya pelan, matanya berbinar dengan sesuatu yang lama tak terlihat: harapan. "Perubahan seperti apa?" tanya Rizky, alisnya berkerut. "Melarikan diri dari sini," jawab Vivi, suaranya kini lebih tegas. "Memulai hidup baru, seperti yang kita impikan dulu. Kita bisa pergi ke mana saja, asal bersama."
Rizky terdiam, matanya menelusuri wajah Vivi seolah mencari kepastian. "Tapi pekerjaan kita? Tagihan? Tanggung jawab?" tanyanya, suaranya penuh keraguan. Vivi tersenyum kecil, tangannya meremas lembut tangan Rizky. "Kita bisa cari kerja di tempat lain. Atau buka usaha kecil-kecilan. Yang penting, kita tidak lagi hidup seperti ini—terkungkung dan lupa caranya untuk bahagia."
Angin malam bertiup lebih kencang, membawa ombak yang sedikit lebih ganas menghantam tepian. Rizky menarik napas dalam, lalu mengangguk perlahan. "Aku bersedia mencoba, asal kamu ada di sampingku." Senyum Vivi melebar, dan dalam senyuman itu, ada janji yang tak perlu diucapkan.
***
Beberapa minggu kemudian, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, sebuah mobil tua melaju perlahan meninggalkan kota kecil itu. Di dalamnya, Rizky memegang kemudi sementara Vivi duduk di sampingnya, sebuah tas sederhana tergeletak di kursi belakang. Mereka tak membawa banyak, hanya pakaian dan sedikit tabungan—tapi juga harapan yang baru saja mereka temukan kembali. Tujuan mereka adalah desa nelayan di pantai barat, tempat yang mereka dengar dari cerita teman lama, di mana hidup berjalan lambat dan laut menjadi sahabat.
Di sana, Rizky mulai mencari nafkah sebagai nelayan, tangannya yang dulu lembut kini penuh kapalan dari menarik jaring. Vivi membuka warung kecil di tepi jalan, menyajikan ikan bakar dan sambal yang mengundang senyum dari para pelanggan. Mereka tak punya rumah besar atau kekayaan melimpah, tapi setiap malam, ketika mereka duduk bersama di depan warung, menatap matahari terbenam yang tak pernah redup, tangan mereka saling bertaut.
"Ini yang kita impikan dulu, kan?" tanya Vivi suatu malam, kepalanya bersandar di bahu Rizky. Ia tak menjawab dengan kata-kata, hanya meremas tangannya lebih erat, tapi itu sudah cukup.