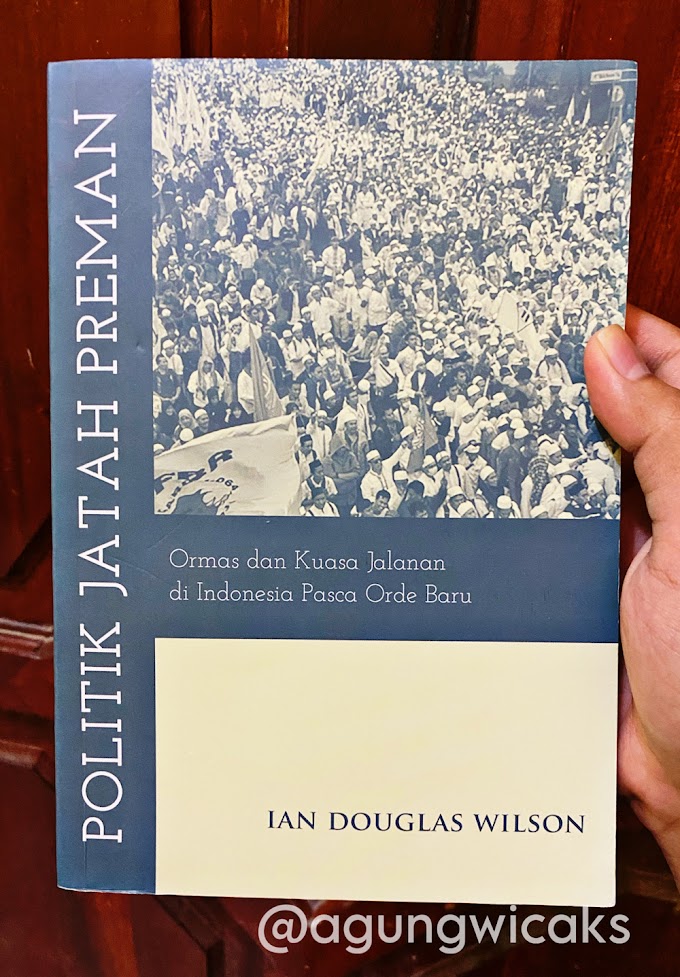Ilustrasi sebuah kafe di mana orang-orang suka menghabiskan waktu bersama atau menikmati kesendirian.
(Sumber gambar: freepik.com)
Di sebuah kafe kecil di sudut Kota Yogyakarta, Dinda duduk sendirian di meja dekat jendela. Cahaya sore menyelinap melalui kaca, menerangi sketsa yang sedang dikerjakannya—gambar Taman Sari yang indah, tempat yang selalu menginspirasi imajinasinya sebagai mahasiswa seni. Rambut hitam panjangnya terikat rapi, dan matanya yang cokelat pekat penuh konsentrasi. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan seorang pemuda masuk dengan langkah ragu, mencari tempat duduk di tengah keramaian.
Pemuda itu mendekat, senyum ramah terukir di wajahnya yang berkulit sawo matang. "Permisi, boleh saya duduk di sini? Kafe ini penuh," tanyanya sopan. Dinda mengangguk, "Tentu, silakan."
Ia memperkenalkan diri sebagai Bima, mahasiswa arsitektur dari Jakarta yang sedang berkunjung ke Yogyakarta untuk mempelajari arsitektur tradisional Jawa. Matanya yang berwarna cokelat keabu-abuan—warna langka yang mungkin diwarisi dari darah campuran Indonesia-Belanda—berkilau penuh semangat saat ia melihat sketsa Dinda. "Bagus sekali gambarnya," pujinya, membuat Dinda tersipu.
Mereka mulai berbincang tentang seni dan arsitektur, dan Dinda merasa nyaman dengan kehadiran Bima. Ada sesuatu pada matanya yang terasa hangat, seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. "Aku suka melihat bangunan tua di sini," kata Bima. "Mau ikut aku ke Kraton dan Taman Sari sore ini?" Dinda tersenyum dan setuju.
Mereka menghabiskan sore itu bersama, berjalan di antara tembok-tembok bersejarah, berbagi cerita tentang impian masing-masing. Bima dengan rambut hitam ikalnya dan senyum yang menawan membuat Dinda merasa dunia berubah sejak pertemuan di kafe itu.
***
Saat matahari mulai tenggelam, langit Yogyakarta berubah menjadi jingga. Mereka duduk di tepi trotoar dekat Taman Sari, menikmati es teh manis. Tiba-tiba, Bima berkata, "Aku harus kembali ke Jakarta besok pagi. Kunjunganku cuma singkat." Suaranya pelan, tapi cukup membuat hati Dinda terasa berat.
Dinda menatap gelasnya, berusaha menyembunyikan kekecewaan. "Oh, cepat sekali," jawabnya singkat. Bima memperhatikan raut wajahnya, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita makan malam bersama nanti? Aku ingin habiskan waktu sebanyak mungkin denganmu."
Malam itu, mereka duduk di sebuah restoran Jawa tradisional. Aroma gudeg dan nasi liwet memenuhi udara, sementara wedang ronde menghangatkan tangan mereka. Percakapan mengalir lebih dalam. Dinda menceritakan impiannya menjadi seniman terkenal, tapi juga ketakutannya akan kegagalan dan luka dari hubungan masa lalu yang membuatnya menutup hati. "Aku selalu takut membiarkan orang masuk," katanya lirih.
Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berbagi ceritanya sendiri. "Aku sering merasa bingung dengan identitasku. Ayahku dari Belanda, ibuku dari Jogja. Kadang aku merasa tidak benar-benar diterima di mana pun." Matanya penuh kejujuran, dan Dinda merasa tembok di hatinya perlahan runtuh.
Di bawah lampu remang restoran, Dinda merasakan kupu-kupu di perutnya—perasaan yang indah tetapi membingungkan. Ia ingin mengenal Bima lebih jauh, tapi bayangan perpisahan esok hari membuatnya ragu. "Apakah ini nyata, atau cuma perasaanku saja?" pikirnya.
***
Setelah makan malam, mereka berjalan di sepanjang jalan Malioboro yang ramai. Tiba-tiba, rintik hujan turun, memaksa mereka berlindung di bawah atap sebuah warung. Di sana, Bima memandang Dinda dan memegang tangannya erat. "Aku nggak mau ini cuma jadi kenangan sehari. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," katanya tulus.
Dinda tersenyum, jantungnya berdegup kencang. "Aku juga, Bima. Aku merasa semua berubah sejak kemarin."
Tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Ia mengangkatnya, dan wajahnya berseri. "Penerbanganku ditunda sampai besok sore karena hujan deras," katanya gembira. Dinda tertawa lega, dan mereka memutuskan untuk menghabiskan hari berikutnya bersama.
Keesokan harinya, mereka mengunjungi Candi Prambanan. Di antara reruntuhan batu kuno, mereka berbagi tawa dan cerita, saling menggenggam tangan. Bima menunjukkan ketertarikannya pada detail arsitektur candi, sementara Dinda menggambar sketsa kecil Bima di buku catatannya. Ikatan mereka semakin erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dinda merasa penuh harapan.
Saat tiba waktunya berpisah di bandara, Bima memeluk Dinda erat. "Aku akan kembali ke Jogja secepat mungkin. Kita jaga komunikasi, ya?" bisiknya. Dinda mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tunggu."
Saat pesawat lepas landas, Dinda berdiri di sana, melambaikan tangan dengan senyum. Ia kembali ke asrama malam itu, membuka ponselnya, dan melihat pesan dari Bima: "Terima kasih untuk hari-hari yang indah. Sampai jumpa lagi, Dinda. Aku akan kembali."
Dengan hati ringan, Dinda menutup mata, tahu bahwa sejak bertemu Bima, segalanya telah berubah.
___________
Kisah ini terinspirasi dari lagu Taylor Swift berjudul Everything has changed.