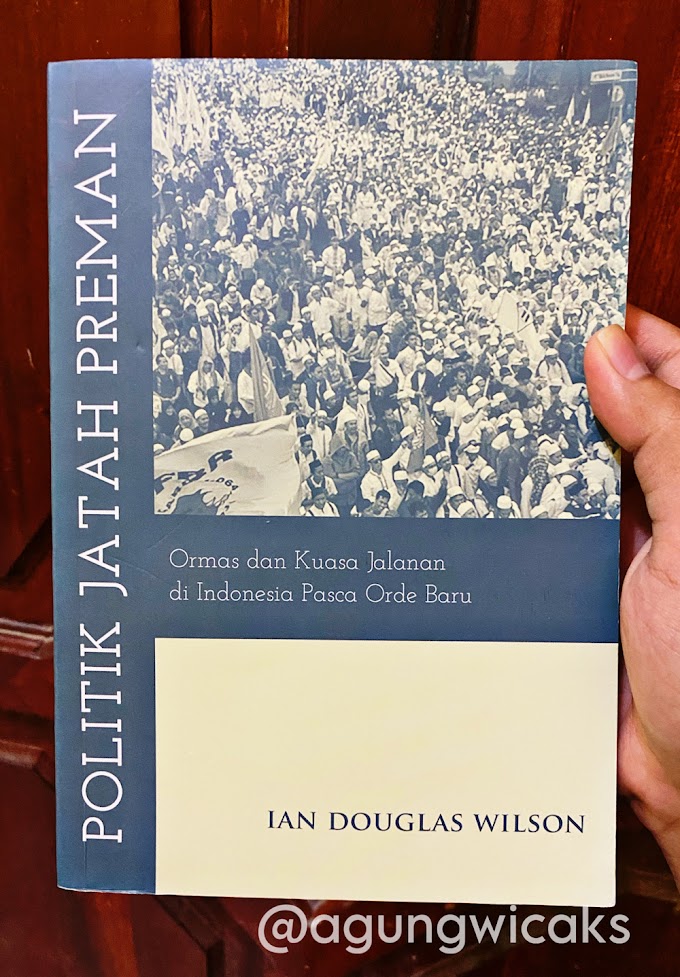(Sumber gambar: freepik.com)
Di apartemen kecil di pinggiran kota, Erwin duduk di depan meja kerjanya yang penuh debu. Ia pernah dikenal sebagai penulis muda berbakat. Kini, ia hanya seorang pria paruh baya dengan rambut mulai memutih dan editor lamban di sebuah penerbitan kecil; menghabiskan hari-harinya mengoreksi naskah orang lain. Di sudut meja, sebuah foto pernikahan tersenyum padanya—istrinya, Shinta, yang telah tiada lima tahun lalu akibat kecelakaan pesawat.
Dulu, Erwin dan Shinta sering duduk bersama di sofa tua mereka, berbagi cerita dan impian. Shinta selalu mengatakan, "Kamu harus menulis novel, Erwin. Novel yang tebal, yang akan membuat orang mengingatmu."
Erwin tersenyum, mengangguk, dan berjanji, "Suatu hari, aku akan menulisnya—untukmu." Tapi hari itu tak pernah tiba. Setelah Shinta meninggal, kata-kata seolah membeku di ujung jarinya. Setiap kali ia mencoba menulis, layar komputer tetap kosong, seperti cerminan hatinya yang hampa.
Sampai suatu sore, keponakannya, Indah, datang berkunjung. Gadis remaja itu membawa energi yang kontras dengan keheningan apartemen Erwin. Dengan tas punggung dan buku catatan di tangan, Indah duduk di sofa dan bertanya, "Paman masih menulis, kan?"
Erwin menggeleng pelan, menghindari tatapan Indah. "Sudah lama tidak, Ndah. Inspirasi itu... hilang."
Indah mengerutkan kening, lalu membuka buku catatannya. "Aku punya ide cerita. Mau dengar?"
"Tentu," jawab Erwin , lebih karena sopan santun daripada minat.
Indah mulai bercerita dengan semangat, "Ada seorang penulis yang kehilangan inspirasinya setelah orang yang ia sayangi meninggal. Ia berjanji akan menulis sesuatu yang hebat untuk orang itu, tapi ia tidak pernah memulainya. Suatu hari, ia bertemu seseorang yang mengingatkannya pada janji itu, dan perlahan, ia menemukan kembali kata-katanya."
Erwin terdiam. Cerita Indah terasa seperti cermin di hidupnya sendiri. "Lalu bagaimana akhirnya?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar.
"Penulis itu menyadari bahwa orang yang ia cintai tidak benar-benar pergi. Mereka ada dalam kenangan, dalam setiap cerita yang pernah mereka bagi. Itu yang membuatnya menulis lagi," kata Indah, matanya berbinar.
Malam itu, setelah Indah pulang, Erwin duduk di depan komputernya. Ia menatap layar kosong, kemudian memejamkan mata. Bayangan Shinta muncul—senyumnya, suaranya yang lembut saat membaca cerita-cerita Erwin dulu. Erwin menghela napas dalam, lalu mulai mengetik.
Kata pertama terasa berat, seperti membuka pintu yang lama terkunci. Tapi begitu kalimat pertama mengalir, yang lain pun menyusul. Ia menulis tentang seorang pria yang kehilangan cinta sejatinya, tentang janji yang terlupa, dan tentang bagaimana kenangan bisa menjadi nyala api yang menyulut kembali semangat. Ia menulis untuk Shinta.
Bulan demi bulan, halaman bertambah. Ketika novel itu akhirnya selesai, Erwin memberinya judul Kenangan yang Abadi dan mendedikasikannya untuk Shinta. Ia mengirimkan naskah itu ke penerbit, dan beberapa bulan kemudian, novel itu terbit. Pembaca menyukainya—mereka terharu oleh kepekaan dan kejujuran di setiap kata.
Saat berdiri di makam Shinta dengan salinan buku di tangan, Erwin berbisik, "Aku menepati janjiku, Shinta. Ini untukmu." Angin berembus lembut, membawa perasaan damai yang lama tak ia rasakan. Ia tahu, di suatu tempat, Shinta tersenyum padanya.