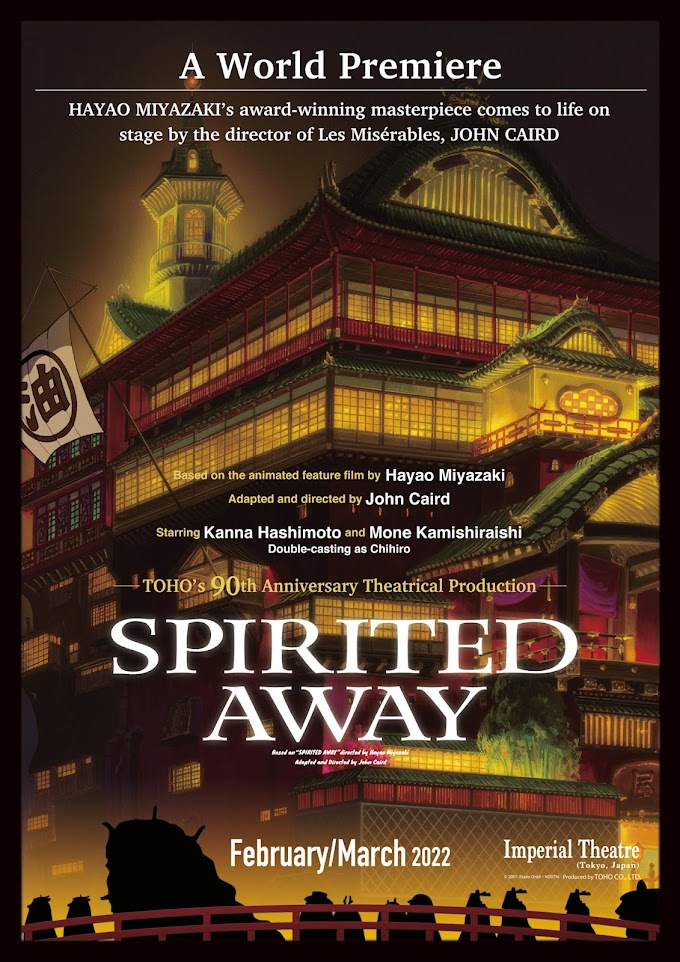Ilustrasi sebuah toko buku.
(Sumber: freepik.com)
Di sudut kota yang ramai, di antara deru kendaraan dan kilau lampu neon, ada sebuah toko buku tua bernama "Halaman Terakhir." Di dalamnya, seorang perempuan duduk di belakang meja kasir, menatap layar komputer dengan mata yang sayu. Namanya Rachel, tiga puluh tahun, rambutnya diikat asal, dan pundaknya terasa berat meski ia tak mengangkat apa pun. Toko itu adalah warisan ayahnya, satu-satunya yang tersisa dari masa lalu yang pernah memiliki banyak harapan. Tapi hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, dering pintu masuk terdengar lebih jarang daripada bunyi napasnya sendiri.
Rachel menggeser jari di layar, memeriksa angka penjualan yang terus merosot. Tumpukan buku di rak-rak berdebu tak lagi menarik perhatian siapa pun. Ia pernah mencoba segalanya: malam baca puisi, obral besar, bahkan mengundang penulis lokal untuk berbagi cerita. Hasilnya? Hanya beberapa wajah penasaran yang datang, lalu pergi tanpa kembali. Di zaman ini, orang lebih memilih ketukan jari di layar ponsel daripada membalik halaman kertas. Rachel menghela napas, merasakan sesuatu menyelinap di dadanya—bukan hanya lelah, tapi juga rasa pasrah yang mulai menggerogoti.
Pintu toko berderit pelan, memecah keheningan. Seorang lelaki masuk, jaket kulitnya usang, tas ransel di pundaknya tampak penuh. Ia berjalan mendekat, senyum kecil mengembang di wajahnya. "Permisi, Anda Rachel?" tanyanya, suaranya hangat tetapi penuh rasa ingin tahu.
Rachel mengangguk, alisnya sedikit terangkat. "Ya, saya Rachel. Ada yang bisa saya bantu?"
Lelaki itu mengulurkan tangan. "Nama saya Ardi. Saya dengar toko ini punya koleksi buku langka."
Senyum tipis muncul di bibir Rachel, sesuatu yang jarang ia rasakan akhir-akhir ini. "Oh, ya, ada beberapa di bagian belakang. Apa yang Anda cari?"
Ardi mengeluarkan selembar kertas dari saku dan menyerahkannya. Rachel melirik daftar judul di sana—buku-buku yang bahkan ia sendiri hampir lupa keberadaannya. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, kecil tapi nyata: harapan.
"Ayo, saya bantu cari," katanya, bangkit dari kursi dengan langkah yang sedikit lebih ringan.
Mereka berjalan ke rak belakang, di mana bau kertas tua menyelinap ke udara. Ardi mengamati setiap judul dengan mata berbinar, jari-jarinya sesekali menyentuh sampul buku seperti menyapa teman lama. Rachel memperhatikannya, merasa ada kehangatan yang aneh menjalar di hatinya. Sudah lama ia tak melihat seseorang begitu tenggelam dalam dunia yang ia cintai.
"Saya dengar toko ini hampir tutup," ujar Ardi tiba-tiba, suaranya lembut tetapi langsung menusuk.
Rachel menegang, tapi tak menjawab segera. Ia mengambil sebuah buku dari rak, membersihkan debu di sampulnya. "Sulit bertahan sekarang. Orang lebih suka baca di gadget."
Ardi mengangguk, matanya tak lepas dari buku di tangan Rachel. "Saya mengerti. Tapi saya percaya masih ada yang menghargai buku fisik. Seperti saya."
Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Rachel menoleh. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang membuat dadanya terasa sedikit lebih lapang.
Mereka melanjutkan pencarian, dan Ardi mulai bercerita. Ia seorang penulis, sedang mengejar inspirasi untuk novel barunya. Buku-buku langka adalah bahan bakarnya, katanya, karena setiap halaman membawa cerita yang tak hanya tertulis, tapi juga tersimpan dalam jejak waktu. Rachel mendengarkan, terpikat oleh cara Ardi berbicara—seperti seseorang yang tak hanya mengejar mimpi, tapi juga memahami bahwa tak semua mimpi sampai tujuan.
Setelah beberapa jam, tumpukan buku di tangan Ardi bertambah. Ia membayar dengan senyum lebar, lalu menatap Rachel sebelum melangkah ke pintu. "Jangan menyerah pada toko ini. Saya yakin masih ada harapan."
Rachel hanya tersenyum, tak yakin harus menjawab apa. Tapi saat Ardi pergi, sesuatu tertinggal di udara—sekecil apa pun, itu cukup membuatnya bertahan sehari lagi.
***
Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Penjualan tetap lesu, tagihan menumpuk, dan Rachel sering mendapati dirinya menatap rak kosong dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Tapi suatu sore, saat menyapu debu dari rak terpencil, jarinya menyentuh sesuatu yang tak biasa. Sebuah buku tua, sampul kulitnya retak, terselip di balik tumpukan lain. Ia menariknya keluar, membukanya, dan napasnya tersendat. Itu jurnal ayahnya.
Halaman demi halaman, tulisan tangan ayahnya mengalir, menceritakan mimpi tentang toko ini—tempat yang penuh tawa, diskusi, dan pengetahuan. Rachel membaca dengan mata berkaca, jari-jarinya gemetar saat menyentuh tinta yang mulai memudar. Di halaman terakhir, ada kalimat yang membuatnya terdiam: "Ketika kamu memiliki mimpi indah tetapi kenyataan berkata lain, ya sudah ambil hikmahnya saja. Namun, jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi adalah awal dari segalanya."
Rachel menutup jurnal, dadanya sesak tetapi ada rasa hangat. Ia menyadari sesuatu: perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang apa yang dulu ayahnya percaya. Ia menggenggam buku itu erat-erat, seperti memeluk semangat yang hampir hilang.
***
Beberapa minggu kemudian, pintu toko kembali berderit. Ardi muncul, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. "Hai, Rachel. Toko buku ini masih buka, kan?"
Rachel mengangguk, ada percikan kecil di matanya. "Masih bertahan, walau susah."
Ardi melangkah masuk, tasnya kali ini lebih ringan. "Saya punya ide. Bagaimana kalau kita adakan acara di sini? Saya bisa ajak teman-teman penulis untuk bicara tentang buku mereka. Dengan harapan pengunjung jadi bertambah banyak juga."
Rachel memandangnya, tak percaya. "Serius? Itu... itu ide bagus."
Mereka mulai merencanakan, duduk di meja kecil dengan kertas dan pena. Ardi berbicara cepat, penuh semangat, sementara Rachel mencatat, tangannya bergerak dengan energi yang sudah lama hilang. Hari demi hari, mereka bekerja bersama, dan Rachel merasa ada ritme baru dalam hidupnya—langkah yang mulai selaras dengan seseorang di sisinya.
***
Pada hari acara, toko dipenuhi suara. Orang-orang datang, duduk di kursi lipat, mendengarkan penulis berbagi cerita. Rachel berdiri di sudut, memperhatikan wajah-wajah yang tersenyum, mendengar tawa yang mengisi ruangan. Matanya bertemu dengan Ardi di seberang ruang, dan lelaki itu mengangguk kecil, seperti mengatakan, "Lihat? Kita bisa."
Setelah semua selesai, Ardi mendekatinya. "Sukses, kan?"
Rachel tersenyum lebar, air mata hampir jatuh tetapi ia bisa menahannya. "Iya. Terima kasih, Di. Aku nggak tahu apa jadinya tanpa kamu."
Ardi menggeleng. "Ini bukan cuma karena aku. Kamu yang nggak nyerah, Rachel. Itu yang bikin beda."
Waktu berlalu, dan "Halaman Terakhir" mulai bernapas lagi. Acara rutin diadakan, pelanggan datang lebih sering, dan Rachel merasa ada pijakan baru di bawah kakinya. Suatu malam, saat ia mengunci pintu toko, Ardi muncul dari bayangan jalanan.
"Rachel, ada yang mau aku katakan," suaranya pelan, sedikit bergetar.
Rachel menoleh, jantungnya tiba-tiba berdegup. "Apa?"
Ardi menarik napas dalam. "Aku menyukaimu. Sejak pertama ke sini, aku merasa ada yang beda sama kamu."
Wajah Rachel memanas, tapi ia tak menoleh pergi. "Aku... aku juga merasa gitu ke kamu," jawabnya, suaranya hampir berbisik.
Ardi tersenyum, lega. "Mau jalan bareng kapan-kapan?"
Rachel mengangguk, bibirnya melengkung. "Mau banget."
Mereka berdiri di sana sejenak, tak bicara, tapi ada kehangatan yang mengalir di antara mereka. Di tengah hidup yang penuh liku, Rachel belajar bahwa tak semua mimpi terwujud seperti yang diinginkan. Tapi di antara reruntuhan harapan, ada kekuatan untuk bertahan, ada tangan yang menawarkan pegangan, dan ada cinta yang tumbuh pelan—realistis, sederhana, tapi nyata.