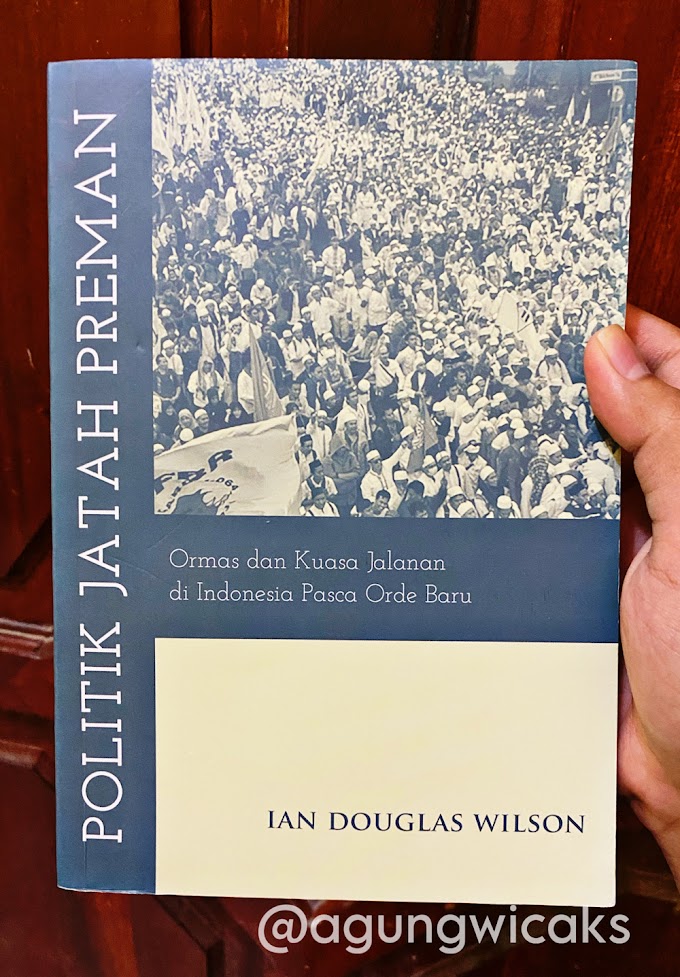Cinta berbeda agama, lalu tidak disetujui oleh keluarga besar masing-masing pasangan, itu sudah sering saya dengar. Eh, ketika sudah seagama, tapi berbeda pemahaman/penafsiran dalam menjalani perintah agama, ternyata cinta pun masih menemui kendala untuk mendapatkan restu keluarga besar. Inilah yang dirasakan oleh Fauzia dan Miftah ketika mereka ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan di dalam novel Kambing dan Hujan.
***
Kisah dimulai ketika Fauzia sudah cukup lama menunggu kedatangan Miftah di dekat halte. Ternyata, ia sudah bersiap sambil membawa tas besar untuk kabur dari rumah; secara tidak langsung berarti kawin lari. Ketika Miftah datang, ia mencoba meyakinkan Fauzia untuk membatalkan rencana tersebut dan mencari cara lain yang lebih baik. Ia khawatir, permasalahan yang dilaluinya akan semakin sulit jika mereka berdua kabur dari rumah, sehingga ia membujuk Fauzia untuk bersama-sama kembali pulang menggunakan motornya.
Setelah rencana yang tidak direalisasikan itu, alur cerita menjadi mundur saat mereka berdua mulai mencari tahu tentang sejarah keluarga masing-masing. Miftah bertanya kepada ayahnya, begitu juga dengan Fauzia. Dari informasi yang mereka dapat, ternyata ayah mereka sudah berteman sejak kecil. Iskandar—ayah Miftah—dan Fauzan—ayah Fauzia—sering menggembala kambing sampai melalui masa pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) bersama. Namun, setelah lulus SR, Iskandar tidak melanjutkan pendidikan karena kekurangan biaya. Ia pun merasa bahwa belajar tidak perlu di sekolah, melainkan bisa belajar secara mandiri. Di masa tersebut, akhirnya ia menemukan guru agama yang dirasa cocok dengan pemahamannya karena dianggap sebagai pembaharu. Sedangkan Fauzan, karena berasal dari keluarga yang mampu, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren. Di sana, ia juga menemukan guru yang cocok dengan pemahamannya dan tetap memegang teguh ajaran agama yang sudah dipraktikkan oleh para pendahulu di desanya. Yang patut disayangkan, perbedaan pemahaman agama yang terjadi di desa semakin lama semakin parah sampai mengakibatkan perkelahian. Hubungan pertemanan antara Iskandar dan Fauzan juga ikut renggang, sehingga mereka jadi jarang bertemu dan bertegur sapa. Selain itu, karena pihak pembaharu ingin mengamalkan ajaran agamanya sesuai yang mereka pahami, mereka pun membangun tempat ibadah baru supaya menghindari perseteruan dari masyarakat yang berbeda. Dengan demikian, di sana terdapat dua tempat ibadah yang jaraknya tidak jauh; masyarakat yang menjalani agama dengan nuansa modern berada di Utara, sedangkan masyarakat yang menjalani agama dengan nuansa tradisional berada di Selatan.
***
Ketika Iskandar dan Fauzan sudah tua, ternyata ketegangan antara dua kubu masyarakat tersebut masih dirasakan sampai ke generasi anak-anaknya. Dari sinilah, ketika mengetahui ternyata kedua anaknya saling mencintai, pembaca akan disuguhkan tentang latar belakang dan kejadian-kejadian lain di masa lalu yang akan mengungkap penyebab perseteruan tersebut; dari mulai kerusuhan ketika salat Jumat sampai kisah cinta yang dialami oleh Iskandar dan Fauzan kepada perempuan yang sama-sama mereka sukai.
Lebih lanjut, membaca novel ini, saya jadi merasakan perjuangan Miftah untuk meyakinkan keluarganya dan juga keluarga Fauzia, begitu juga Fauzia yang berusaha membujuk kedua orang tuanya agar merestui hubungan mereka. Padahal, agama mereka sudah sama, yang membuatnya susah adalah ketika gengsi masih menyertai kedua belah pihak; ayah mereka seperti tidak mau mengalah dan tidak mencoba untuk mencari titik temu dari kejadian tersebut. Dengan demikian, peristiwa itu membuat saya menyadari bahwa toleransi memang sangat dibutuhkan dalam menjalankan perintah agama; bukan hanya kepada yang berbeda, tetapi juga yang seagama.